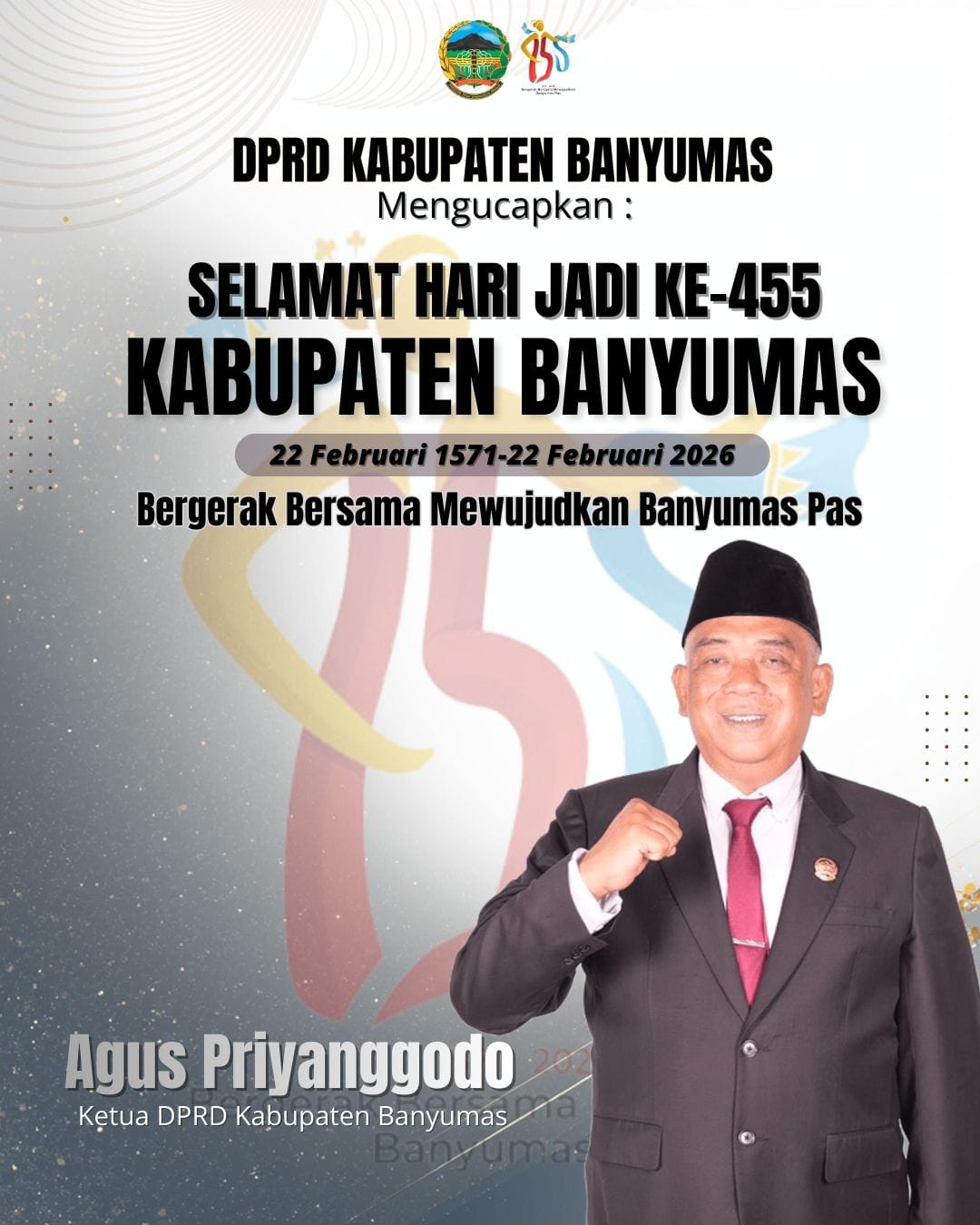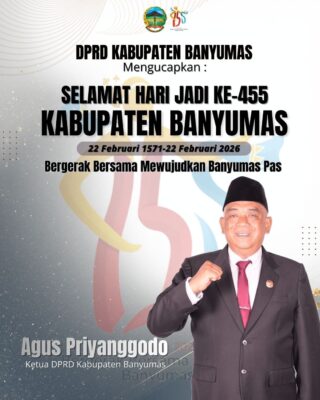![]()
Memahami Gagasan-gagasan Besar Sang Proklamator (1)
Ada tiga peristiwa besar bagi bangsa Indonesia yang jatuh pada bulan ini. Pertama, tokoh bangsa yang jasanya tak terhingga, Bung Karno, lahir di Surabaya Tanggal 1 Juni 1901. Pada tanggal yang sama di tahun 1945, dia yang telah menjadi tokoh perjuangan bangsa ini, diminta untuk menyampaikan gagasannya tentang Pancasila dalam sidang Dokuritsu Junbi Cosakai (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan). Secara aklamasi, BPUPKI menyetujui gagasan Bung Karno yang kita pegang teguh hingga detik ini sebagai dasar Negara Indonesia.
Minggu pagi pukul 07.00 waktu Jakarta, tanggal 21 Juni 1971, Bung Karno wafat. Bapak bangsa dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Jakarta. Petang hari itu, jenazah Bung Karno dimakamkan di Blitar. Duka menyelimuti segenap bangsa Indonesia, mereka pun mengibarkan bendera Merah Putih setengah tiang. Bung Karno, wafat persis 15 hari setelah ulang tahunnya yang ke-69. Ketiga peristiwa itulah yang kemudian kita kenal sebagai Bulan Bung Karno.
Mumpung diberi ruang untuk beropini, dari menelusuri banyak literasi, saya memilih jalur lain dalam upaya menginterpretasi gagasan-gagasan besar Bung Karno. Salah satunya menuliskan apa yang beliau gagas untuk negeri ini, dengan harapan nan begitu besar agar seluruh elemen bangsa tak akan pernah lupa akan sejarah yang telah ditorehkan oleh Bung Karno. Dari waktu ke waktu, hingga apa yang ia wariskan bagi bangsa Indonesia tidak akan pernah lekang oleh zaman. Pancasila adalah warisan besar dari sekian warisan yang beliau berikan untuk bangsa ini, dan bukan sembarang warisan-warisannya yang hanya dibuat tanpa buah pemikiran nan cemerlang.
Bung Karno sejatinya mulai mengelaborasi gagasan-gagasan yang membentuk marhaenisme pada tahun 1920-an. Kala itu, ada tigas gagasan besar yang mempengaruhi gerakan revolusi nasional Indonesia: marxisme, nasionalisme dari bangsa tertindas, dan Islamisme yang anti-kolonial. Bung Karno muncul dengan gagasan yang disebutnya Marhaenisme. Sebuah ajaran yang elektis dan secara menyeluruh mengandung sifat daripada subjektifitas dan idealisme.
Kata Marhaen, konon merujuk kepada nama seorang petani kecil yang ditemui Soekarno. Marhaenisme, jika kita lihat dari urian Bung Karno di tulisan ”Marhaen dan Proletar”, adalah sebuah analisa terhadap klas-klas sosial dalam relasi produksi mayarakat Indonesia. Dalam buku otobiografinya yang ditulis Cindy Adams, Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, diceritakan tentang sosok Marhaen Ketika Bung Karno menemui sosok petani itu di wilayah Jawa Barat.
“Siapa yang punya semua yang engkau kerjakan sekarang ini,” tanya Soekarno.
“Saya, juragan,” jawab si petani.
“Apakah engkau memilih tanah ini bersama-sama dengan orang lain?”
“O.. tidak, gan. Saya sendiri yang punya.”
“Tanah ini kau beli?”
“Tidak. Warisan bapak kepada anak turun-temurun.”
Soekarno merenung sejenak. Pikirannya sibuk meresapi jawaban petani tersebut. Lalu, karena masih belum terang, ia kembali mengajukan pertanyaan.
“Bagaimana dengan sekopmu? Sekop ini kecil, tapi apakah kepunyaanmmu juga?
“Iya, gan,” jawab si petani.
“Dan cangkul?”
“Iya, gan?”
“Bajak?”
“Saya punya, gan.”
“Untuk siapa hasil yang kau kerjakan?”
“Untuk saya, gan.”
“Apakah cukup dengan kebutuhanmu?”
“Bagaimana sawah yang begini kecil bisa cukup untuk seorang isteri dan empat orang anak?” keluh petani itu.
“Apakah ada yang dijual dari hasilmu?”
“Hasilnya sekedar cukup untuk makan kami. Tidak ada lebihnya untuk dijual.”
“Kau mempekerjakan orang lain?”
“Tidak, juragan, saya tidak dapat membayarnya.”
“Apakah engkau pernah mem-buruh?”
“Tidak, gan. Saya harus membanting-tulang, akan tetapi jerih-payah saya semua untuk saya.”
Bung Karno Ketika melakukan riset sebagai pijakan dari gagasan yang ia ciptakan, tak hanya melakukan pendataan di kalangan petani, tapi juga terhadap tukang gerobak dan rakyat jelata lainnya.
Mengutip dari laman berdikarionline.com, riset itu mengantarkan Soekarno pada sebuah kesimpulan: mayoritas rakyat Indonesia (konon, 90% saat itu) adalah pemilik alat produksi kecil, dengan perkakas kerja kepunyaan sendiri, tidak mempekerjakan tenaga orang lain (dikerjakan sendiri bersama anggota keluarga), dan hasilnya hanya cukup untuk diri sendiri dan keluarganya.
Soekarno kemudian menjadikan Marhaen sebagai prototipe dari kaum pemilik produksi kecil ini.

Penulis: H Bambang Pudjiyanto